

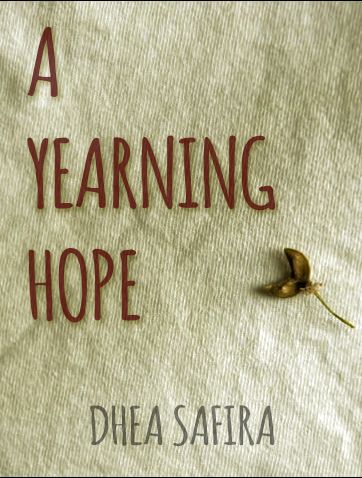
“Pada akhirnya, pilihan kita justru jatuh pada tteokbokki, jjajjangmyeon, dan soda. Ck, padahal aku ingin membelikanmu makanan yang lebih mahal.”
Aku tersenyum menanggapi kata-kata suamiku. Kusandarkan kepalaku pada bahunya dengan manja. “Apa yang kita makan tidaklah penting. Yang terpenting adalah dengan siapa kita makan. Dan, selama ada Oppa di sisiku, itu sudah lebih dari cukup.”
Suamiku mengelus lembut puncak kepalaku yang tertutupi kerudung. “Aku memang beruntung memiliki istri pengertian sepertimu, Joo Hye Rim,” katanya, yang sukses membuat pipiku merona. “Omong-omong, apa tidak sebaiknya kita segera berbuka? Perutku sudah meneriakkan protes sejak tadi.”
Ah, benar. Aku sampai lupa jika perutku belum kemasukan apa pun kecuali sebutir permen yang tadi aku makan sebelum sholat Magrib. Lekas kuambil dua mangkuk jjajjangmyeon berbahan styrofoam di depanku. Satu kuberikan pada suamiku.
Malam ini kami berbuka di sebuah taman yang terletak di dekat Sungai Han, beralaskan rumput yang baru saja dipangkas serta beratapkan langit kota Seoul yang penuh bintang. Satu kata untuk momen ini: romantis.
Sungguh, aku bersedia mempertaruhkan seluruh tabunganku demi bisa menikmati momen ini setiap hari. Yah, walau uang tabunganku memang tidak seberapa.
“Bagaimana rasanya menjadi mahasiswa jurusan arsitektur?” Suamiku bertanya.
“Sedikit berat pada awalnya. Aku harus membiasakan diri dengan jadwal kuliah yang padat. Tapi semuanya menyenangkan,” sahutku. “Kira-kira, saat kelulusanku nanti, apakah Oppa bisa datang?”
Suamiku mendesah pelan. Respons itu membuatku tertunduk lesu secara refleks.
“Hei, jangan begitu. Kau membuatku merasa bersalah.” Suamiku menyentuh daguku, membuatku mendongak ke arahnya. “Aku akan mengusahakan supaya bisa datang. Lagipula, kau baru saja kuliah. Tidakkah terlalu dini membicarakan kelulusan?”
Mau tidak mau, aku tersenyum menanggapi kalimatnya. Benar juga. Terkadang, aku suka sekali berpikiran terlalu jauh.
“Ah, aku baru ingat. Ada sebuah rumah makan halal yang baru buka di daerah Hongdae. Sahur nanti, bagaimana kalau kita coba makan di sana?”
Aku mengangguk.
“Andai setiap bulan adalah Ramadan, aku pasti senang.” Suamiku bergumam.
Aku mengiakan dalam hati. Baik aku dan suamiku tahu betapa berartinya bulan Ramadan bagi kami.
*****
Beberapa hari lagi, Ramadan datang. Sama seperti kebanyakan muslim di dunia, aku pun menantikan momen itu. Yah, walau puasa kali ini terjadi saat musim panas, dimana aku harus menahan hawa nafsu selama kurang lebih 17 jam. Jujur saja, itu tidaklah mudah. Apalagi jika kau berada di antara orang-orang yang bahkan tidak tahu apa itu puasa.
Kusandarkan punggungku pada sebuah pohon besar seraya menyelonjorkan kaki. Lapangan ini adalah salah satu tempat favoritku di kampus. Di sini, aku bisa mengistirahatkan otakku sejenak dari peliknya rutinitas kampus yang membuat kepala berguncang.
Perhatianku teralih pada buku catatan bersampul kuning berbahan beledu yang sedang aku pegang.
Selamat Ulang Tahun, istriku tercinta.
Dari suamimu, yang selalu mencintaimu.
-Lee Dong Wook-
Kedua sudut bibirku tak kuasa terangkat, tiap kali membaca pesan pembuka yang ada dalam buku catatanku. Suamiku satu itu memang selalu punya cara untuk membuat darahku berdesir.
Saat membuka sebuah halaman secara acak, aku kembali tersenyum. Sebuah foto tertempel di situ. Foto suamiku yang tampak bahagia dengan semangkuk patbingsu di tangannya dan aku yang masih terbalut seragam sekolah. Di bawahnya ada sebuah catatan kecil yang kutulis: ‘Buka puasa pertama dengan suami’.
*****
Aku menikah ketika aku masih kelas 3 SMA. Banyak yang menganggapku gila karena mau-mau saja dinikahi oleh seorang musisi tak terkenal yang penghasilannya tak seberapa. Meski begitu, menerima pinangan Dong Wook Oppa adalah sesuatu yang tidak pernah aku sesali. Bersamanya, hidupku terasa sempurna–walau banyak kesulitan yang harus kami hadapi.
Kali pertama aku buka puasa dengan suamiku, kami memilih pergi ke Seoul Central Mosque. Di tempat itu, telah banyak orang-orang berkumpul, menanti waktu berbuka. Tak hanya warga asli Korea, aku juga menjumpai orang-orang dari luar Korea seperti Indonesia, Malaysia, hingga Turki.
Aku dan suamiku menunggu di pelataran masjid. Kami duduk di bawah naungan sebuah pohon. Kami mengobrol seputar kegiatan kami hari ini hingga tak terasa azan telah berkumandang.
Mendengar azan berkumandang di saat puasa adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagiku. Rasanya, aku seperti mendapat undian berhadiah rumah semiliar. Dulu, sewaktu kecil, aku selalu menunggu azan di halaman depan rumah. Dan, aku menjadi yang paling histeris saat azan berkumandang. Kebiasaan yang masih berlanjut hingga kini.
“Rasa-rasanya, patbingsu tidak pernah terasa seenak ini sebelumnya,” kata suamiku, yang tengah lahap menghabiskan patbingsu-nya.
“Itulah salah satu nikmatnya puasa. Makanan yang sebelumnya kita anggap biasa-biasa saja, akan jadi superlezat.”
Suamiku mencubit pipiku lembut sebagai respons atas kata-kataku tadi. Senyum manisnya merekah sempurna. Lalu, ia berkata, “Kau benar. Kalau begini caranya, aku tidak keberatan jika kita harus berpuasa setiap harinya.”
Sebuah ide tahu-tahu melintas di otakku. “Oppa, ayo kita berfoto!” Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas lalu mulai mengatur sudut penggambilan gambar yang tepat.
Aku tersenyum puas ketika melihat hasil jepretanku.
“Hye Rim-ah.”
Aku melepaskan pandanganku dari layar ponsel begitu suamiku memanggil. Kedua alisku bertaut ketika mendapati ekspresi suamiku yang berubah gelisah. Sepertinya, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya.
“A-da apa?” tanyaku, yang jadi ikut-ikutan gelisah.
“Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu.”
Suamiku tak langsung menyelesaikan kalimatnya. Agaknya ia ragu antara ingin mengatakannya atau tidak. Jujur saja, itu membuatku tidak tenang. Suamiku adalah orang yang periang. Karena itu, mendapatinya dalam keadaan seperti ini membuatku cemas.
“Aku... Ah, nanti saja kita bicarakan. Kita sholat Magrib dulu. Lihat itu, orang-orang sudah mulai masuk masjid.”
Namun, sisa hari itu hingga beberapa hari berikutnya, suamiku tak kunjung mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Hal itu membuatku diserang rasa penasaran sekaligus khawatir. Entah kenapa, intuisiku mengatakan ada hal tidak menyenangkan yang akan terjadi.
Dan, begitu suamiku mengatakan apa yang ingin ia katakan, duniaku serasa berguncang. Rupanya, intuisiku sedang bekerja dengan baik. Dan, aku benci itu.
*****
Aku kembali membuka halaman demi halaman buku catatanku, hingga pada akhirnya tiba pada sebuah halaman yang menampilkan sebuah daftar tulisan. Aku dan suamiku selalu menyusun daftar kegiatan apa saja yang ingin kami lakukan selama bulan puasa. Mulai dari apa yang kita lakukan untuk menunggu waktu berbuka puasa, apa yang kita makan saat buka puasa, di mana kita akan buka puasa, apa yang kami lakukan seusai sholat tarawih, hingga apa yang akan kita makan saat sahur.
Selama puasa, kami selalu berbuka di luar. Itu adalah kemauan suamiku. Menurutnya, dengan berbuka puasa di luar–terutama di kawasan yang banyak muslimnya–akan membuat suasana Ramadan terasa lebih kental.
Makan japchae dan permen kapas, jalan-jalan di Hongdae, makan es krim, sahur dengan bibimbap.
Aku tersenyum sendiri kala membaca beberapa daftar yang aku tulis. Kadang, keinginanku memang kelewat aneh. Namun, seaneh apa pun keinginan yang aku tulis, suamiku tidak pernah mengeluh sedikit pun dan selalu memenuhinya.
Aku kembali membalik halaman-halaman berikutnya, dan dibuat tercenung selama beberapa saat begitu menemukan sesuatu. Sesuatu tersebut adalah daftar kegiatan yang ingin aku lakukan pada puasa dua tahun lalu.
Tiba-tiba saja perasaan sedih menyerangku.
“Buatlah daftar kegiatan apa saja yang ingin kau lakukan selama puasa nanti. Saat itu tiba, aku akan memenuhi apa pun yang kau tulis,” kata suamiku kala itu.
Aku ingat betul bagaimana antusiasnya diriku ketika menulis daftar kegiatan itu. Terasa ironis ketika pada akhirnya aku justru dilanda kesedihan tiap kali teringat daftar-daftar yang aku buat.
*****
Sesuai rencana, aku dan suamiku makan sahur di salah satu rumah makan halal yang ada di Hongdae. Beberapa orang sudah duduk manis di meja ketika kami masuk ke rumah makan tersebut.
Rumah makan ini menjual makanan khas Indonesia. Atas saran dari pemilik rumah makan, kami memilih nasi rawon, sate telur, dan es beras kencur. Karena keterbatasan tempat duduk, kami pun harus berbagi meja dengan pengunjung lain.
“Rasanya seperti kembali ke kampung halaman ketika menikmati masakan Indonesia di negara orang.” Seorang laki-laki yang duduk di sebelah suamiku tiba-tiba saja mengajak kami mengobrol. Aku dibuat terkejut oleh bahasa Koreanya yang fasih.
Orang itu lalu bercerita bagaimana suasana puasa di Indonesia. “Di Indonesia, para pedagang makanan dan minuman akan menggelar lapak mereka sehabis asar. Suanasa akan ramai seperti di pasar. Dan itu, sungguh adalah pemandangan yang menyenangkan.”
Suamiku dan orang itu terlibat pembicaraan seru setelahnya. Aku hanya menyimak penuh antusias. Mengetahui bagaimana puasa di negara lain adalah sesuatu yang menarik bagiku.
“Saat sahur, TV swasta akan berlomba menyuguhkan tontonan yang menghibur, yang membuat sahur jadi lebih hidup,” kata orang itu. “Kadang, ada beberapa komunitas yang mengadakan sahur on the road. Biasanya, mereka membagikan makanan pada mereka yang kekuarangan.”
Dan, pembicaraan orang itu dan suamiku berlangsung hingga kami selesai menikmatip makanan yang kami pesan.
Seusai menghabiskan makanan, aku dan suamiku jalan-jalan sebentar di sekitar Hongdae–sambil menunggu subuh menjelang. Berbeda dengan biasanya, kali ini Hongdae cenderung lebih lengang. Hanya beberapa orang saja yang melintas di sekitar kami. Saking lengangnya, aku bahkan bisa mendengar dengan jelas suara desah napasku.
“Mendengar cerita orang tadi, aku jadi ingin meraskaan puasa di Indonesia,” kataku. “Sahur on the road bersama sepertinya menyenangkan.”
Tanpa kuduga, suamiku mendekap bahuku. “Memangnya, sahur berdua denganku tidak menyenangkan?”
Aku mencubit pinggangnya, membuatnya tergelak. “Tidak ada yang lebih menyenangkan dari menghabiskan waktu bersama Oppa.”
“Aigoo, aku jadi terharu,” katanya, pura-pura tersentuh dengan ucapanku.
“Seandainya, aku bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama Oppa. Tidak hanya ketika puasa dan lebaran saja.”
Aku tahu jika ini adalah topik sensitif di antara kami. Kami mencoba sebisa mungkin untuk tidak membahas masalah ini. Entah angin apa yang membuatku tiba-tiba saja membicarakan masalah ini.
“Hye Rim-ah....” Suamiku menghentikan langkahnya. Ia berbalik menghadapku. Kedua tangannya menggenggam tanganku, matanya menatapku intens. “Kau tahu persis mengapa aku melakukannya. Semua ini demi masa depan kita.”
“Aku tahu. Maaf. Harusnya aku tidak mengatakannya,” sahutku lemah. “Hanya saja, terkadang aku masih merasa sulit menghadapi situasi ini.”
Tangan suamiku beralih untuk merangkup pipiku. “Situasi ini juga sulit bagiku. Bersabarlah sebentar lagi. Saat itu tiba, aku pastikan aku akan selalu berada di sisimu.”
Saat itu tiba. Entah kapan tepatnya.
Aku pun mengangguk mengerti. Lalu, kami melanjutkan jalan-jalan kami menyusuri jalanan Hongdae sambil bergandengan tangan.
Kelak, ketika keinginan kecilku itu terkabul, aku justru mendapat kejutan lain. Kejutan yang sama sekali tidak kuinginkan.
*****
Dulu, satu hal yang kurindukan dari bulan Ramadan adalah suasananya. Aku bingung bagaimana harus mendeskripsikannya, yang jelas suasana ketika Ramadan berbeda dengan hari-hari biasanya. Lebih tenang, lebih nyaman, dan sebagainya.
Aku rindu momen dimana aku menunggu azan magrib dengan penuh antusias, lalu berseru penuh semangat ketika tiba waktunya berbuka. Aku juga merindukan ketika aku bisa sholat tarawih bersama keluarga, ketika mendengar ayat-ayat Quran dibacakan, atau ketika sahur menjelang.
Ketika menikah, kebiasaan itu masih terus berlanjut. Meski tak seramai sewaktu di rumahku dulu, namun menjalankan puasa berdua dengan suamiku tak kalah menyenangkan. Kami memiliki kebiasaan menulis daftar kegiatan apa saja yang ingin kami lakukan selama bulan puasa.
Kami yang memang hobi berwisata kuliner, memutuskan untuk bertualang dari satu restoran halal ke restoran halal yang lain. Sambil menunggu berbuka, kami biasanya menghabiskan waktu untuk mengobrol santai.
Tak jarang, kami menghabiskan waktu buka puasa di kafe tempat suamiku tampil. Pekerjaannya sebagai penyanyi kafe membuat suamiku kadang pulang hingga pagi menjelang. Terkadang, saat aku libur sekolah, aku menemani suamiku hingga selesai tampil. Setelahnya, kami akan mencari tempat untuk sahur.
Kebiasaan kami lainnya ketika puasa tiba adalah kami tak pernah melewatkan patbingsu. Rasa dingin dan manis yang menjalar di lidah seakan mengobati dahaga kami selama 17 jam berpuasa.
Hatiku selalu bergetar ketika mengingat momen-momen manis itu. Kini, ketika Ramadan sebentar lagi akan datang, aku sungguh berharap momen-momen manis itu bisa kembali terulang. Aku begitu merindukan momen-momen itu.
Aku sudah menulis beberapa daftar kegiatan yang ingin aku lakukan pada Ramadan kali ini. ‘Makan patbingsu di taman dekat Sungai Han’, ‘Berjalan-jalan di sekitar Dongdaemun’, well, hal-hal seperti itu.
Namun, di atas semua itu, ada satu hal yang benar-benar aku inginkan. Satu hal yang aku berharap akan benar-benar terjadi.
*****
“Apa?” Aku bertanya sekali lagi, memastikan aku tidak salah dengar. Aku baru saja pulang dari sekolah. Seperti biasa, suamiku telah menyambutku dengan senyum sehangat musim gugurnya. Namun, kata-kata yang tadi dikatakannya benar-benar membuat kepalaku mendadak berguncang, seolah baru saja terjadi gempa teknonik yang mahadahsyat. “Oppa, kau tidak sedang bercanda, kan?”
Suamiku menggeleng lemah.
Jadi, aku tidak salah dengar. Bahwa suamiku menerima pekerjaan sebagai musisi di kapal pesiar adalah sebuah kebenaran. Juga, soal ia yang hanya diberi libur selama satu bulan dalam rentang satu tahun.
“Itu artinya.... Oppa akan meninggalkanku sendirian di rumah ini?”
Baru beberapa bulan aku menikah dan kini aku harus menghadapi ancaman maut seperti ini. Benar-benar menyebalkan.
“Bukan begitu.” Suamiku mencoba menenangkanku yang mulai terguncang. “Ini hanya sementara, sampai aku mendapat penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga kita. Mereka memberikan gaji yang cukup tinggi. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini.”
“Selama ini, walau hidup kita sederhana, kita tidak pernah merasa kekurangan. Kenapa tiba-tiba Oppa membutuhkan banyak uang?”
Suamiku menyuruhku duduk, walau enggan, aku pun menurut. Ia mendekap bahuku dengan lembut. “Kontrak menyanyiku di kafe akan segera berakhir dan mereka tidak berencana memperpanjangnya. Sedangkan kebutuhan hidup semakin lama semakin tinggi. Ditambah, sebentar lagi kau akan kuliah–”
“Sudah kubilang, aku tidak perlu kuliah.” Aku menyela. “Itu hanya akan membuang-buang uang. Lebih baik aku bekerja–”
“Kau harus kuliah.” Giliran suamiku yang menyela. “Kau pintar dan berbakat. Kau tidak boleh menyia-nyiakan otakmu. Lagipula, aku sudah janji pada orangtuamu untuk menguliahkanmu.”
Aku ingin protes tetapi suamiku mendahului. “Bukankah kau bilang ingin mendesain rumah impian kita? Kita bangun mimpi itu bersama-sama. Kau yang merancang, aku yang mencari uang. Begitu kan rencana kita?”
“Tetapi, jika itu membuatku tidak bisa bersama Oppa, apa Oppa pikir aku akan bahagia?”
Suamiku menggenggam jemariku. Ia menatapku penuh kelembutan. “Apa kau pikir aku juga bahagia dengan pilihan ini?”
Aku menggeleng.
“Terkadang, ada hal-hal yang harus kita korbankan demi mencapai sesuatu. Sebentar saja, kita korbankan kebersamaan kita. Hanya sebentar. Demi masa depan kita dan anak kita nantinya. Kau, mengizinkanku, kan?”
Hati kecilku mengatakan tidak, tentu saja. Namun, kelembutannya membuat pertahananku goyah. Ini adalah kali pertama Oppa memohon sesuatu dariku. Aku merasa jahat jika tidak bisa mengabulkan permintaannya.
Akhirnya, dengan berat hati aku mengizinkannya menerima tawaran itu.
“Aku pastikan akan pulang ketika puasa datang. Aku akan meneleponmu setiap hari. Meski kita berjauhan, hati kita tetap akan saling berdekatan. Benar, kan?” tanyanya, lalu merengkuhku dalam pelukannya.
Aku mengangguk. Tanpa bisa kucegah, air mataku menitik perlahan.
*****
Sejak suamiku menerima tawaran untuk menyanyi di kapal pesiar, praktis aku selalu menunggu supaya bulan Ramadan cepat datang. Rasanya, aku tidak pernah serindu ini dengan bulan Ramadan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, aku jadi lebih antusias menyambut Ramadan.
Suatu ketika, suamiku menjemputku pulang kuliah. Itu adalah saat ketika suamiku mendapatkan libur untuk pertama kalinya setelah bekerja hampir setahun. Seperti biasa, kami jalan-jalan sebentar sambil menunggu saat berbuka tiba. Tidak seperti biasanya, suamiku mengajakku ke pantai.
“Sebenarnya, ada kejutan yang ingin kusampaikan padamu.”
Aku mengernyit. “Kejutan? Kejutan apa?”
Suamiku tampak berpikir sejenak. “Kontrakku akan berkahir pada puasa tahun depan. Dan, aku memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi kontraknya.”
“Kenapa?” tanyaku.
“Tabunganku sudah cukup banyak. Selain itu, seorang teman menawarkan kerja sama padaku. Prospeknya cukup bagus.”
“Jadi?” Aku menggantungkan kalimatku.
“Jadi, mulai puasa tahun depan aku tidak akan lagi meninggalkanmu sendirian di rumah.”
Aku tidak bisa menjelaskan perasaan apa saja yang bercampur dalam hatiku. Rasanya, seperti baru saja menemukan sebuah harta karun yang sangat berharga. Kalau tidak ingat sedang berpuasa, aku pasti akan langsung menghambur ke pelukannya sambil menangis tersedu-sedu.
*****
Namun rupanya, semesta belum mengabulkan keinginanku. Aku mendapat kejutan beberapa hari setelah suamiku kembali berlayar. Kapal yang ditumpangi suamiku menabrak karang dan akhirnya tenggelam. Beberapa orang telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Namun, masih ada beberapa orang yang belum ditemukan; suamiku salah satunya.
Kejadian itu terjadi dua tahun lalu. Dan, sampai sekarang, belum ada kejelasan tentang bagaimana nasib suamiku. Keluarga dan teman-temanku memintaku untuk mengikhlaskan. Aku benci dengan sikap mereka yang seolah menganggap suamiku telah tiada.
Sebut aku bodoh, tetapi selama tidak ada jasad suamiku, aku masih percaya jika dia masih hidup. Aku tidak pernah lelah untuk menunggunya pulang, seperti yang dulu dijanjikannya padaku.
“Tunggu aku, aku pasti pulang. Aku janji. Ah, aku jadi tidak sabar menantikan puasa tahun depan. Padahal, puasa baru saja berakhir beberapa hari yang lalu,” katanya waktu itu. “Kuharap, kau menulis kegiatan-kegiatan yang mengasyikkan. Jangan lupa, jaga kondisimu, jangan biarkan stres menghampiri. Selama menunggu kepulanganku, tetaplah semangat menjalani hidup. Fighting!”
Aku ingat betul bagaimana ekspresi bahagianya kala itu, seolah ia adalah manusia paling bahagia di dunia. Setelah itu, ia memelukku. Aku ingat ia sempat berbisik padaku. Katanya, “Aku merindukanmu sebesar aku merindukan bulan puasa.”
Sesaat sebelum naik kapal, dia minta kami berfoto. Sesuai keinginannya, kami berfoto bersama. Satu di ponselku, satu di ponselnya.
Foto itulah yang kini sedang kupandangi. Foto yang kutempel di buku catatanku, yang selalu kupandangi tiap harinya. Kusentuh foto itu dengan perasaan campur aduk. Rasa rindu adalah yang paling mendominasi.
Tatapanku lalu tertuju pada daftar kegiatan yang baru saja aku tulis. Daftar kegiatan yang aku ingin lakukan pada puasa tahun ini. Dan, hal pertama yang aku tulis–sama seperti dua tahun ini–adalah bertemu dengan Dong Wook Oppa.
Hanya itu.
Aku tak peduli jika tak bisa makan patbingsu dan sebagainya. Asal aku bisa bertemu dengan Dong Wook Oppa, itu sudah lebih dari cukup.
Sama seperti puasa dua tahun ini, aku masih tetap percaya bahwa suamiku akan pulang. Dan, saat itu terjadi, aku akan memeluknya erat dan mengatakan betapa beruntungnya aku punya suami sepertinya.
Saat itu terjadi.
Entah puasa tahun ini, tahun depan, atau entah kapan.
Sampai saat itu terjadi, aku akan tetap menunggunya pulang. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak berhenti berharap.
Bahwa, suatu saat nanti, suamiku akan kembali pulang.